
Alokasi Anggaran Pendidikan...
JPPI mengkritik alokasi anggaran pendidikan dalam...
Mekanisme hukum yang ideal harus memisahkan dengan jelas antara fiktif positif dan fiktif negatif. Fiktif positif diselesaikan melalui mekanisme internal pemerintahan, pengawasan oleh Ombudsman dan APIP, serta dukungan digitalisasi. Sementara itu, fiktif negatif tetap berada di bawah otoritas PTUN untuk melindungi hak konstitusional warga negara.

Negara hukum mengharuskan pemerintah untuk melayani warganya dengan adil, transparan, dan responsif. Namun dalam praktiknya, permohonan dari warga negara seringkali tidak mendapat respon dalam waktu yang wajar, yang kemudian menimbulkan fenomena sikap diam dari pemerintah. Sikap ini, yang dianggap sebagai maladministrasi, berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.
Secara hukum, sikap diam pemerintah dapat dibagi menjadi dua jenis: fiktif negatif (penolakan diam) dan fiktif positif (persetujuan diam). Fiktif negatif, yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diperbarui dalam UU No. 51 Tahun 2009, menyatakan bahwa jika permohonan tidak dijawab dalam batas waktu yang ditentukan, permohonan tersebut dianggap ditolak. Sementara itu, fiktif positif, yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menganggap diamnya pemerintah sebagai bentuk persetujuan.
Sayangnya, peraturan yang mengatur kedua jenis fiktif ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum.
Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, maladministrasi mencakup tindakan aparat negara yang tidak sesuai dengan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau pengabaian kewajiban hukum. Bentuk maladministrasi yang sering terjadi dalam pelayanan publik adalah tidak memberikan pelayanan atau penundaan yang tidak wajar.
Data Ombudsman RI pada tahun 2023 mencatat lebih dari 1.300 laporan terkait ketiadaan pelayanan, serta hampir 1.000 laporan tentang penundaan yang berlarut. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam integritas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Dari sudut pandang konstitusional, tindakan maladministrasi ini jelas bertentangan dengan hak-hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, seperti hak kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 27 Ayat 1), hak atas kepastian hukum (Pasal 28D Ayat 1), hak atas informasi (Pasal 28F), serta hak bebas dari diskriminasi (Pasal 28I Ayat 2).
Sikap diam pemerintah yang berujung pada maladministrasi memiliki dampak serius terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Negara, seharusnya, memiliki tiga kewajiban utama dalam konteks HAM, yakni memberikan pelayanan publik yang layak (to fulfill), tidak membuat kebijakan yang merugikan warga (to respect), dan menindak pejabat yang melakukan pelanggaran (to protect).
Untuk itu, sebuah mekanisme hukum yang ideal harus dibangun dengan memisahkan secara tegas antara fiktif positif dan fiktif negatif. Fiktif positif harus diselesaikan melalui mekanisme internal pemerintahan dengan pengawasan dari Ombudsman dan APIP, serta didukung dengan digitalisasi. Sedangkan fiktif negatif tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memastikan perlindungan hak konstitusional warga.
Namun dalam praktiknya, banyak permohonan dari warga yang tidak mendapatkan tanggapan atau diproses dengan sangat lambat. Akibatnya, hak atas pelayanan publik yang adil dan transparan menjadi sekadar impian. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai, sikap diam pemerintah bisa berujung pada penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat.
Setelah diberlakukannya UU Peratun, sikap diam pemerintah dianggap sebagai fiktif negatif, yang artinya apabila pejabat tidak memberikan jawaban atas permohonan dalam batas waktu yang ditentukan, permohonan tersebut dianggap ditolak. Hal ini memungkinkan warga untuk menggugat keputusan tersebut ke PTUN sesuai dengan Pasal 3 UU Peratun.
Namun, UU AP memperkenalkan konsep baru berupa fiktif positif, di mana diamnya pemerintah dianggap sebagai persetujuan. Konsep ini semula dianggap progresif karena mendorong birokrasi untuk lebih responsif terhadap permohonan warga.
Namun, kekacauan mulai muncul setelah disahkannya UU Cipta Kerja yang menghapus kewenangan PTUN untuk menguji fiktif positif. Kini, penyelesaian masalah ini hanya dapat dilakukan melalui mekanisme internal pemerintahan, meskipun belum ada Peraturan Presiden yang mengatur lebih lanjut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja. Akibatnya, warga sering terjebak dalam ketidakpastian hukum—harus menggugat ke PTUN atau menunggu tanggapan dari pemerintah yang tidak jelas.
Perbedaan norma ini menyebabkan dua masalah besar: ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang dapat berlindung di balik ketidakjelasan regulasi.
Untuk menangani sikap diam pemerintah yang merupakan bagian dari maladministrasi, perlu ada pembedaan yang jelas antara penyelesaian fiktif positif dan fiktif negatif. Penyelesaian fiktif positif harus dilakukan melalui mekanisme internal pemerintah, dengan pengawasan lebih ketat oleh Ombudsman dan APIP.
Mekanisme hukum yang ideal harus memisahkan secara tegas antara fiktif positif dan fiktif negatif. Fiktif positif harus diselesaikan melalui mekanisme internal pemerintah dan pengawasan oleh Ombudsman dan APIP, serta mendukung digitalisasi. Fiktif negatif tetap menjadi kewenangan PTUN untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga.
Untuk itu, perlu adanya pengembangan digitalisasi dalam pelayanan publik, seperti OSS dalam perizinan usaha, agar permohonan yang memenuhi syarat dapat diproses secara otomatis tanpa bergantung pada sikap pejabat.
Penyelesaian fiktif negatif tetap berada dalam otoritas PTUN, sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa sikap diam pejabat yang tidak memberikan keputusan dalam kasus tertentu harus dipandang sebagai penolakan yang dapat digugat ke PTUN.
Beberapa negara maju, seperti Prancis dan Kanada, telah berhasil mengatasi masalah sikap diam pemerintah. Di Prancis, setiap keputusan fiktif positif dicatat secara resmi di situs pemerintah, sehingga menjamin transparansi. Di Kanada, portal digital terpusat digunakan untuk memfasilitasi permohonan warga secara otomatis kepada instansi terkait.
Indonesia dapat meniru praktik tersebut dengan membangun sistem e-Government Service yang terintegrasi, yang tidak hanya mempercepat layanan tetapi juga mengurangi peluang maladministrasi akibat sikap diam pemerintah.
Sikap diam pemerintah merupakan ancaman nyata bagi perlindungan hak konstitusional warga negara. Maladministrasi yang timbul akibat sikap diam—seperti tidak memberikan pelayanan atau penundaan yang berlarut—merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Mekanisme hukum yang ideal harus memisahkan secara tegas antara fiktif positif dan fiktif negatif. Fiktif positif diselesaikan melalui mekanisme internal pemerintahan dengan pengawasan oleh Ombudsman dan APIP, serta didukung dengan digitalisasi. Sedangkan fiktif negatif tetap menjadi otoritas PTUN untuk memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Kerancuan norma yang ada semakin memperburuk keadaan, terutama setelah UU Cipta Kerja mencabut kewenangan PTUN atas fiktif positif. Ketidakpastian hukum ini membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat.
Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan publik dapat kembali melayani masyarakat dengan adil, transparan, dan responsif, serta menjadikan negara hukum Indonesia benar-benar melindungi hak-hak warganya.
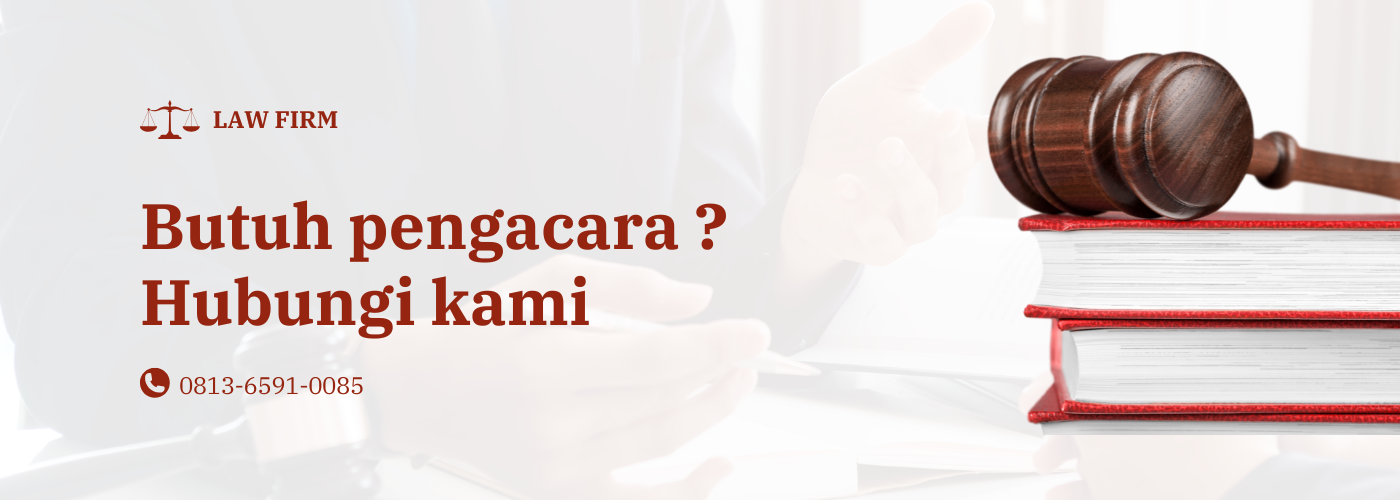

02 Sep 2025
Tom Lembong sebelumnya mengajukan laporan...

19 Aug 2025
Mengenal lebih jauh tentang notaris,...

19 Aug 2025
Mengenal lebih jauh tentang notaris,...

